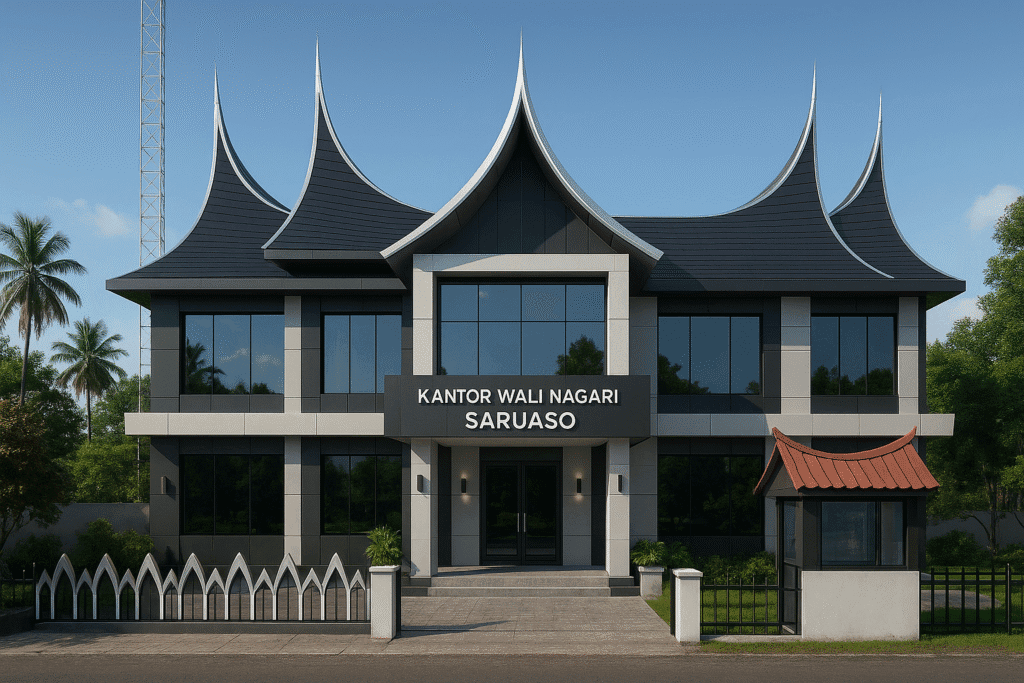Sejarah Saruaso
- Periode Prasejarah
Menulis sejarah Nagari Saruaso dari periode prasejarah sampai dengan periode terkini merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan berat. Hal itu disebabkan karena penulis hidup pada abad kedua puluh. Kondisi itu dipersulit lagi tidak adanya sumber-sumber terpercaya dan teruji secara ilmiah. Menurut penulis, sejarah Nagari Saruaso tidak terlepas dari sejarah Minangkabau, dimulai pada kurun waktu antara abad pertama Masehi dengan abad ketujuh (periode prasejarah) karena Nagari Saruaso merupakan bagian dari Minangkabau.
Adi Sastra (2013) mengemukakan yang dimaksud dengan zaman mula sejarah Minangkabau ialah zaman yang meliputi kurun waktu antara abad pertama Masehi dengan abad ketujuh. Di mana dengan adanya berita-berita tertulis tertua mengenai Minangkabau seperti istilah San-Fo Tsi dari berita Cina yang dapat dibaca sebagai Tambesi yang terdapat di Jambi. Di daerah Indonesia lainnya juga sudah terdapat berita atau tulisan seperti kerajaan Mulawarman di Kutai Kalimantan dan Tarumanegara di Jawa Barat. Namun dari berita-berita itu belum banyak yang dapat diambil sebagai bahan untuk menyusun sebuah ceritera sejarah, karena memang masih sangat sedikit sekali dan masing-masingnya seakan-akan berdiri sendiri tanpa ada hubungan sama sekali. Pada kondisi yang demikian, Soekomono memberikan nama zaman Proto Sejarah Indonesia, yaitu peralihan dari zaman prasejarah ke zaman sejarah.
Apabila dicermati Tambo dan ceritera rakyat untuk menemukan mula sejarah Saruaso dan Minangkabau secara keseluruhan, kita tidak akan pernah mendapat jawaban. Hal itu dikarenakan Tambo dan ceritera rakyat menyebutkan: ”…tatkalo maso dahulu, dari tahun musim baganti, dek zaman tuka-batuka, dek lamo maso nan talampau, tahun jo musim nan balansuang, antah barapo kalamonyo…”. Dari ungkapan waktu yang demikian memang sulit sekali menentukan kapan terjadinya. Pengertian zaman dahulu itu mengandung banyak kemungkinan tafsiran dan sangat relatif.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa cerita mula sejarah nagari Saruaso amatlah gelap. Kita tidak mempunyai sumber sama sekali, bukan hanya gelap akan tetapi sudah gelap gulita.
B. Periode Sejarah
Sejarah tentang Saruaso baru dapat diketahui pada periode sejarah. Informasi yang ditemui rasanya belumlah memadai namun sudah sangat membantu sekali untuk mengetahui sedikit tentang sejarah Saruaso. Beberapa sumber yang dapat dipedomani antara lain:
- Prasasti Saruaso I, Prasasti Saruaso II, dan Prasasti Batu Bapahek
Sebelum kita mengetengahkan cerita dan isi Prasasti Saruaso I, Prasasti Saruaso II, dan Prasasti Batu Bapahek, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu tentang ekpedisi Pamalayu yang melatarbelakangi sejarah Saruaso.
Ekpedisi Pamalayu merupakan perjalanan historis dan politis oleh kerajaan Singasari di pulau Jawa ke pulau Sumatera. Penjelasan ekpedisi Pamalayu ditemui pada Prasasti Dharmmasraya. Prasasti ini dipahatkan pada lapik Arca Amoghapasa di jorong Sungai Langsek, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya. Lapik arca tersebut merupakan lapik Arca Amoghapasa yang ditemukan di Padangroco, yang sampai saat ini tidak dapat diketahui penyebab terpisahnya lapik arca itu, sementara Arca Amoghapasa yang diperuntukkan bagi Tri Bhuwana Mauliwarmmadewa dipakai oleh Adityawarman untuk membuat prasasti (sebagai media peringatan) pada punggung Arca Amoghapasa.
Budi Istiawan (2014) menyebutkan bahwa pada tahun 1208 S (1286 M), bulan Badrawada tanggal 1 paro terang, Arca Amoghapasa dibawa dari Bhumi Jawa yang ditempatkan di Dharmmasraya. Arca ini merupakan persembahan dari Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara (dari kerajaan Singasari di Jawa) untuk Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa dari Melayu Dharmmasraya. Adapun pejabat yang mengiringi pengiriman arca ini dari Bhumi Jawa adalah Rakryan Adwayabrahma, Rakryan Sirikan Dyah Sugatabrahma dan Samgat Payangan hang Dipangkara Rakryan Dmung pu Wira. Persembahan ini merupakan bentuk jalinan persahabatan antara kerajaan Singasari di Jawa dan Kerajaan Melayu Dharmmasraya di Sumatera, yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Lebih lanjut Budi Istiawan (2014) menyatakan bahwa yang menarik dikaji dari prasasti di atas adalah penyebutan nama pejabat pengiring Arca Amoghapasa, yaitu Rakryan Adwayabrahma. Nama Adwayabrahma muncul di dalam Prasasti Kubu Rajo I dan merupakan ayah kandung Raja Adittyawarman. Dengan demikian, jelas bahwa Adwayabrahma, seorang pejabat tinggi di Kerajaan Singasari akhirnya dikawinkan dengan salah seorang putri Melayu bernama Dara Jingga dan mempuntai anak yang disebut sebagai Aji Mantrolot atau Tuhan Janaka (dalam kitab Pararaton) atau Adityawarman.
Darah Jingga, bersama dengan Darah Petak, merupakan gadis Melayu yang dibawa dan diperkenankan oleh para utusan Singasari sebagai bentuk kesepakatan adanya persahabatan dan persekutuan antara Melayu dan Singasari. Darah Petak kemudian dikawinkan dengan Raden Wijaya, menantu Kartanegara dan kemudian menjadi pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit, sesudah runtuhnya Kerajaan Singasari. Adapun Darah Jingga dikawinkan dengan Adwayabrahma dan melahirkan Aji mantrolot atau Tuhan Janaka. Tuhan Janaka yang lahir dan besar di Jawa ini kemudian sempat menduduki jabatan Wrdhamantri pada masa Raja Hayamwuruk dan Bersama dengan Mahapatih Gajah Mada membesarkan dan mengharumkan Kerajaan Majapahit, yang wilayah kekuasaannya sampai ke mancanegara. Tuhan Janaka atau Adityawarman ini pada akhirnya kembali ke tanah ibunya di Kerajaan Melayu dan memerintah sebagai seorang Raja Melayu Dharmmasraya yang berpusat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari (wilayah sekitar Desa Rambatan dan Sungai Langsek, kecamatan Sitiwung, kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat).
Sekaitan dengan hal tersebut, Adi Sastra, (2013) mengemukakan bahwa tahun 1275, Raja Kertanegara dari kerajaan Singosari mengirimkan suatu ekspedisi militer ke Sumatera dalam rangka melemahkan kekuasaan Sriwijaya dan memperluas pengaruhnya di Nusantara. Ekspedisi ini dikenal dalam sejarah Indonesia dengan nama ekspedisi Pamalayu. Sebagai hasil dari ekspedisi Pamalayu, tahun 1286 Kertanegara mengirimkan arca Amogapasa ke Sumatera sebagai hadiah untuk raja dan rakyat kerajaan Melayu. Dengan pengiriman arca Amogapasa ini dapat diartikan bahwa antara kerajaan Singosari dan kerajaan Melayu sudah terjalin hubungan baik dan saling membantu apabila salah satu mendapatkan serangan dari pihak asing.
Selesai ekspedisi, rombongan ekspedisi kembali ke Jawa, mereka membawa Dara Jingga dan Dara Petak. Sesampai di Jawa kerajaan Singasari telah diganti oleh kerajaan Majapahit. Maka Dara Petak diambil sebagai selir oleh Raden Wijaya raja pertama kerajaan Majapahit. Dari perkawinan ini lahir Jayanegara raja kedua Majapahit. Sedangkan Dara Jingga kawin dengan salah seorang pembesar kerajaan Majapahit dan melahirkan seorang putera yang nama kecilnya Aji Mantrolot. Aji Mantrolot ini yang kemudian dikenal sebagai Adityawarman. Dengan demikian Adityawarman merupakan keturunan dari dua darah kaum bangsawan, satu darah bangsawan Sumatera dan satu darah bangsawan Majapahit. Di keraton Majapahit Adityawarman di didik bersama saudara sepupunya Jayanegara dan menduduki jabatan salah seorang menteri. Jabatan ini diperolehnya bukan saja karena hubungan darahnya dengan raja Majapahit tetapi juga berkat kecakapannya sendiri. Tahun 1325 raja Jayanegara mengirim Adityawarman sebagai utusan ke negeri Cina yang berkedudukan sebagai duta. Bersama dengan Patih Gajah Mada, Adityawarman ikut memperluas wilayah kekuasaan Majapahit di Nusantara. Tahun 1331 Adityawarman memadamkan pemberontakan Sadeng dengan suatu perhitungan yang jitu. Tahun 1332 dia dikirim kembali menjadi utusan ke negeri Cina dengan kedudukan sebagai duta. Pada tahun 1334 Adityawarman pulang kembali ke negeri asalnya. Karena dengan lahir dan menjadi besarnya Hayam Wuruk tidak ada lagi kesempatan bagi Adityawarman untuk menjujung mahkota kerajaan Majapahit sebagai ahli waris yang terdekat.
Adi Sastra (2013) melanjutkan, Adityawarman adalah cucu dari raja Melayu karena ibunya Dara Jingga adalah anak Tribuana raja Mauliwarmadewa, raja kerajaan Melayu. Oleh karena itu, Adityawarman berhak atas takhta kerajaan Melayu tersebut. Timbulnya keinginan Adityawarman untuk mendirikan kerajaan Melayu yang mandiri, disebabkan karena kegagalan usaha patih Gajah Mada menguasai selat malaka. Pada tahun 1347 Adityawarman menjadi raja kerajaan Melayu yang dipusatkan di Darmasraya. Hal ini dapat dibuktikan dengan prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Amogapasa dari Padang Candi. Dalam Prasasti itu Adityawarman memakai nama “Udayadityawarman Pratakramarajendra Mauliwarmadewa” dan bergelar “Maharaja Diraja” dengan memakai gelar tersebut rupanya Adityawarman hendak menyatakan bahwa dia merupakan raja yang berdiri sendiri dan tidak ada lagi raja yang berada di atasnya. Dengan demikian dia sudah bebas dari Majapahit. Sebagai realisasi dari pernyataan tersebut, maka Adityawarman pada tahun 1349 memindahkan pusat kerajaan dari Darmasraya ke Saruaso.
Mengenai pusat kerajaan Adityawarman berada di Saruaso tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut berdasarkan tafsiran dan penjelasan Budi Istiawan (2014) tentang Prasasti Saruaso I, Prasasti Saruaso II dan Prasasti Batu Bapahat dan Dodi Chandra (2013) tentang Prasasti Saruaso I, Prasasti Saruaso II dan Prasasti Saruaso (Batu Bapahek). Namun saja mungkin dalam pikiran pembaca timbul pertanyaan mengapa ke Saruaso dan tidak ke tempat lain?. Hal ini dapat dijelaskan minimal dari empat alasan. Pertama. Adityawarman adalah orang yang dididik dan dibesarkan di Majapahit dan pernah menjabat beberapa jabatan penting, tentulah paham betul dengan seluk beluk pemerintahan seperti strategi, ekonomi, sosial budaya dan sumber-sumber pendapatan kerajaan. Dengan demikian Adityawarman tentu memilih daerah yang kaya dengan sumber daya alam, dan sumber daya alam terpenting itu adalah emas yang terkandung dalam bumi Saruaso.
Kedua, Ramlan Cs (1995) dalam sejarah Tanah Datar mengungkapkan bahwa pada abad ke 14 dan 15 penduduk Minangkabau telah giat dalam perdagangan lada dan emas. Patner dagang penduduk Minangkabau adalah pedagang India Selatan (Tamil) dan pedagang Gujarat.
Daerah-daerah penghasil lada antara lain Kamang dan Tanjuang (Luhak Agam) sedang daerah-daerah penghasil emas antara lain Buo, Sumpur Kudus, Saruaso, Unggan, Mandiangin, Manganti, Salido, Bayang, Tarusan, Bandar sepuluh, Indrapura dan Ophir. Buo, Sumpur Kudus dan Saruaso merupakan penghasil emas utama.
Ramlan Cs (1995) melanjutkan bahwa emas yang ditambang di Saruaso disalurkan melalui pantai barat melewati Simawang. Di Simawang jalan bercabang dua. Pertama ke arah utara dimana terdapat jalan tembus ke Pariaman, lebih dikenal dengan jalan Jawi. Kedua ke arah selatan melewati Saningbakar, menaiki Bukit Barisan dan setelah turun di Pauh akhirnya sampai di Padang.
Ketiga, Di Saruaso terdapat situs budaya Makam Raja-raja Saruso yang telah dipugar dan dilestarikan oleh BPCB Sumbar, Riau dan Kepri. BPCB Sumbar, Riau dan Kepri memiliki para peneliti dan Arkeolog yang handal, dan tentunya tidak sembarangan menentukan suatu objek menjadi objek sejarah yang patut dipugar dan dilestarikan.
Keempat. Salah satu jorong di Saruaso bernama jorong Sungai Ameh. Pemberian nama Sungai Ameh tentu pula berhubungan dengan situasi dan kondisi daerah. Berdasarkan tuturan orang tua-tua bahwa memang dulu di Sungai Ameh dan sekitarnya banyak terdapat emas.
Sekarang mari kita membicarakan Prasasti Saruaso I, Prasasti Saruaso II dan Prasasti Saruaso (Batu Bapahek) sebagai dasar dari sejarah Saruaso.
Sebagian masyarakat Saruaso menyebut Prasasti Saruaso I adalah Batu Basurek, terletak di Kampuang Rajo jorong Saruaso Barat. Terdapat beberapa ahli sejarah yang menulis tentang Prasasti Saruaso I. Kern, (1917) menginterpretasikan Prasasti Saruaso tahun 1375 sebagai berikut: Dalam tahun caka 1279 bulan Jyaista, pada hari selasa….dengan tanda-tanda kebesaran seorang raja terkemuka, maka raja Adityawarman telah menjadikan kesatriannya dengan nama “Vicelat Dharani”, Tuan dari Suravase, duduk di atas kursi tinggi, sambil menyantap makanan lezat dan minuman di luar istana. Puluhan dan ratusan bunga harumnya menyebar ke mana-mana, harum semerbak sesajian Raja Adityawarman tiada taranya. Sedangkan terjemahan Moens berbunyi: Dalam tahun 1297 caka dalam bulan maut Raja Adityawarman menerima tasbihan Bhairawa tertinggi di sebuah lapangan mayat (dengan itu ia bebaskan hidup, hidup dijadikan bhumityaga, kesatriannya) dengan nama “Vicelat Dharani”, sambil bersemayam dengan sunyi senyap di atas sebuah tempat duduk….
Sekaitan dengan itu Budi Istiawan (2014) menjelaskan Prasasti Saruaso I masih in situ (masih tetap berada di tempat aslinya) bersama dengan beberapa artefak kecil lainnya dan sekarang telah diberi cungkup pelindung. Prasasti ini ditulis dengan huruf Jawa Kuno dan bahasa Sanskerta dengan ukuran tinggi 75 cm, panjang 133 cm, dan lebar 110 cm. Prasasti Saruaso I berasal dari Raja Adittyawarman yang berangka tahun 1297 Saka atau 1375 M, berisi suatu pengabaran tentang upacara keagamaan yang dilakukan oleh Raja Adittyawarman sebagai seorang penganut Budha Mahayana sekte Bhairawa. Upacara itu merupakan pentasbihan dirinya sebagai Wisesa Dharani (salah satu perwujudan Budha) di suatu kuburan yang disebut dengan Surawasan atau sekarang menjadi Saruaso.
Selanjutnya tentang Prasasti Saruaso II. Saat ini Prasasti Saruaso II berada di depan Gedung Indo Jolito dan dikumpulkan bersama srtefak lainnya. Prasasti Saruaso II dipahatkan pada sebuah batu pasir kwarsa warna coklat kekuningan pada kedua belah sisinya. Batu prasasti ini berbentuk empat persegi berukuran tinggi 110 cm, lebar 75 cm, dan tebal 17 cm. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari isi prasasti ini yakni, pertama penyebutan yauwa raja Ananggawarmman atau raja muda anak dari Raja Adittyawarman. Kedua, penyebutan nama yauwa raja Bijayendrawarman yang mendirikan stupa di Parwatapuri (Prasasti Lubuk Layang) nagari Pancahan kabupaten Pasaman mengindikasikan sistem pemerintahan kerajaan Melayu Kuno (masa Adittyawarman?) menyerupai sistem pemerintahan masa Kerajaan Majapahit. Mengingat keberadaan prasasti Lubuk Layang yang jauh dari pusat kerajaan Adittyawarman di Saruaso, mungkin sekali bahwa yauwa raja Bijayendrawarman berkuasa di sekitar prasasti, tetapi kekuasaannya tetap berada di bawah kendali Raja Adittyawarman (Budi Istiawan: 2014).
Uraian berikutnya tentang Prasasti Saruaso (Batu Bapahek). Prasasti Suruaso yang juga dinamakan dengan Prasasti Batu Bapahek merupakan salah satu dari prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman. Prasasti ini dinamakan Prasasti Suruaso karena pada manuskripnya tersebut kata Sri Surawasa yang merupakan asal kata dari nama nagari Suruaso. Prasasti Suruaso dipahatkan pada bahagian kiri dan kanan saluran irigasi Batang Selo, menggunakan aksara Melayu dan sebuah lagi menggunakan aksara Nagari (Tamil). Pembangunan saluran irigasi ini dapat menunjukan kepedulian Adityawarman untuk peningkatan taraf perekonomian masyarakatnya dengan tidak bergantung dengan hasil hutan dan tambang saja. Dodi Chandra (2013) menafsirkan teks Prasasti Suruaso yang beraksara Melayu menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya. Dr. Uli Kozok berpendapat bahwa hal tersebut memastikan bahwa adat Minangkabau, yaitu pewarisan dari mamak (paman) kepada kamanakan (keponakan), sesungguhnya telah terjadi pada masa tersebut.
C. Masa Pemerintahan Sultan Alif
Dari uraian di atas, Suravase/Surawasan/Surawasa dan Saruaso adalah suatu daerah/nagari yang merupakan pusat pemerintahan di dataran tinggi Minangkabau pada zaman Adityawarman, telah memulai dan memiliki peradaban semenjak abad ke 13 dan memiliki peranan penting di zamannya serta memiliki catatan sejarah pajang dalam estalase kebudayaan Minangkabau.
Abad ke 16 (tahun 1560) Kerajaan Minangkabau dipimpin oleh Sultan Alif yang beragama Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Alif terwujud Sumpah Satie Bukit Marapalam yang melahirkan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, sistem pemerintahan Kerajaan Minangkabau bercorak desentralisasi berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang lazim disebut “Tungku Nan Tigo Sajarangan” dengan sistim nilai yang disebut “Tali Tigo Sapilin”. Dengan Sumpah Satie Bukit Marapalam, kerajaan Minangkabau dipimpin oleh “Rajo Nan Tigo Selo” (Raja Alam dibantu oleh Raja Adat dan Raja Ibadat) dengan “Basa Ampek Balai” nya (Dewan Menteri).
Ramlan Cs, (1995) menyatakan Basa Ampek Balai berkedudukan di empat nagari yakni: a) Dt. Bandaro di Sungai Tarab sebagai pimpinan, b) Tuan Khadi di Padang Ganting sebagai pemegang masalah agama, c) Tuan Indomo di Saruaso sebagai pemegang masalah keuangan, dan d) Tuan Machudum di Sumanik sebagai pemegang masalah pertahanan.
Berdasarkan keterangan/informasi yang diperoleh, yang memegang fungsi Indomo antara lain: a) Indomo I bernama Tombo Regan, b) Indomo II bernama Tombo Ani, c) Indomo III bernama Puti Amalia, dan d) Indomo IV bernama Rajo Imbang (wawancara dengan Ibu Sani salah seorang keturunan Indomo).
Dari uraian di atas, Saruaso adalah kampung halaman Indomo dan merupakan tempat kedudukan salah seorang Basa Ampek Balai dengan jabatan Menteri Keuangan Kerajaan Minangkabau.
D. Tambo Alam Minangkabau
Ada baiknya juga dikemukakan cerita yang terdapat dalam Tambo Alam Minangkabau yang menurut ahli sejarah menggolongkannya sebagai legenda. Pencantuman Tambo ini setidaknya sebagai bahan pembanding bagi generasi muda Saruaso. Diceritakan dalan Tambo bahwa penduduk Minangkabau adalah keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain yang merupakan raja termashur dari Macedonia (336 SM-323 SM). Ketika Sultan Iskandar Zulkarnain memerintah Macedonia maka disuruh anak bungsunya yang bernama Maharaja Diraja berlayar ke Selatan. Kapal yang ditumpangi Maharaja Diraja beserta isteri dan pengikutnya ini kemudian terdampar di Gunung Merapi. Lama kelamaan air mulai turun dan dibuatlah pemukiman di pinggang gunung tersebut. Pemukiman ini mereka sebut dengan Pariangan. Asal usul orang Minangkabau ditemui dalam mamang adat yakni “Dari mano asa titiak palito, dibaliek telong nan batali, tarang bulan bamego-mego, cahayo manyambuah ka tangah padang, dari mano asa niniak kito, dari lereng gunung merapi, turun ka galundi nan baselo, iyo di daerah Pariangan Padang Panjang”.
Kemudian Tambo menyebutkan pertambahan penduduk yang makin lama terus meningkat, memaksa nenek moyang berusaha mencari tempat pemukiman baru dan menyusun aturan dan norma untuk dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan dan norma itu dikenal dengan kata “Lareh atau Sistim Adat”. Terdapat tiga Lareh di Minangkabau yaitu Lareh Koto Piliang, Lareh Bodi Caniago, dan Lareh Nan Panjang. Setiap Lareh memiliki daerah sendiri-sendiri. Daerah yang termasuk Lareh Koto Piliang ialah Sungai Tarab Salapan Batua, Simawang-Bukik Kanduang, Labuatan-Sungai Jambu, Batipuah-Sapuluah Koto, Singkarak-Saning Baka, Tanjuang Balik-Sulik Aia, Silungkang-Pandang Sibusuak, Pagaruyuang, Saruaso, Ata, Padang Gantiang, Taluak Tigo Jangko, Pangian, Buo, Batua, Talang Tangah, Gurun, Ampalu, Minangkabau, Simpuruik, Sijangek, Sabu, Andaleh, Pitalah, Bungo Tanjuang, Tanjuang Barulak, Batu Taba, Guguak, Malalo, Guguak Padang Laweh, Koto Piliang, Sumaniak, Sungai Patai, dan Gunuang Rajo.
Dari uraian di atas, Saruaso telah ada ketika nenek moyang menerapkan sistim adat atau lareh untuk mengatur kehidupan masyarakat pada periode awal perkembangan daerah-daerah di Minangkabau.
E. Kejayaan raja-raja kecil di Saruaso
Disamping Tambo, diketengahkan pula cerita kearifan lokal masyarakat Saruaso terutama yang berkembang di kalangan orang tua-tua. Bakhtiar (2009) mengemukakan bahwa dulunya Saruaso meliputi dua nagari yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang raja. Pertama, Nagari Bala Labuah Balai Aua yang didiami oleh suku Sumpu, Malayu, Piliang, dan Caniago dipimpin oleh Rajo Balai Awua dibantu empat orang Kapalo Suku. Kedua, Nagari Bala Labuah Tanjuang Balik yang didiami oleh suku Mandahiliang, Kutianyia, Bendang, dan Ambacang Lilin dipimpin oleh Rajo Balai Awua dibantu empat orang Kapalo Suku. Kapalo Suku pembantu kedua raja tersebut dikenal dengan nama Penghulu Suku atau Panghulu Nan Salapan.
Rajo Tanjuang Balik dengan Rajo Balai Aua selalu berebut pengaruh bahkan berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kondisi ini sangat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pertikaian kedua Rajo tadi sampai sekarang masih ada bekasnya walaupun nagari sudah bersatu, seperti lobang lahat kuburan dan bungkus lapek. Lobang lahat di daerah kekuasaan Rajo Tanjuang Balik dibuat di sebelah matahari terbit, sedangkan lobang lahat di daerah kekuasaan Rajo Balai Aua dibuat di sebelah matahari terbenam. Bungkus lapek di daerah kekuasaan Rajo Tanjuang Balik dengan bungkus lapek di daerah kekuasaan Rajo Balai Aua juga berlawanan arah.
Untuk mengatasi pertikaian antara Rajo Tanjuang Balik dengan Rajo Balai Aua maka Panghulu Nan Salapan beserta cerdik pandainya mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah disepakati untuk memindahkan Rajo Tanjuang Balik ke Bukit Gombak. Rajo Tanjuang Balik diantar bersama-sama dan di sebuah bukit Rajo diajak bermain catur sehingga bukit itu sekarang bernama “Bukit Percaturan”. Dalam perjalanan tersebut sang Rajo merasa haus dan berhenti dekat sebuah sumur atau luak. Ketika Rajo meminum air luak rupanya air luak tidak enak atau anyia dan Rajo tidak jadi meminumnya. Luak itu sampai sekarang bernama “Luak Anyia”.
Setelah lama berjalan akhirnya Rajo beserta rombongan pengantar sampai di suatu tempat dekat perbatasan Saruaso dengan Pagaruyuang. Tempat itu sekarang dikenal dengan “Sawah Uluran”. Di lokasi ini lah kedua Rajo dipertemukan dengan Panghulu Nan Salapan beserta pengikut-pengikutnya oleh Raja Pagaruyung Sultan Alif II sekitar abad ke 17. Kedua Rajo dianjurkan untuk mengakhiri pertikaian karena telah merugikan rakyat ke dua belah pihak. Anjuran tersebut sesuai pula dengan ajaran Islam yang telah dianut oleh yang dipertuan Raja Alam Sultan Alif II dan masyarakat Minangkabau.
Kedua raja di soru supaya oso atau dianjurkan untuk berdamai dan bersatu. Rajo Tanjung Balik diperintahkan mengurus agama dan ibadah sedangkan Rajo Balai Aua diperintahkan mengurus adat istiadat. Sehingga anak nagari beribadah menurut agama Islam dan melaksanakan adat istiadat secara benar. Dengan demikian adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus ditinggalkan sebagaimana isi Sumpah Satie Bukit Marapalam yakni “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Dari uraian di atas, Saruaso berasal kata soru dan oso, yakni nasehat Sultan Alif kepada Rajo Tanjuang Balik dan Rajo Balai Aua agar berdamai dan bersatu untuk bersama-sama membangun nagari.
F. Periode Sejarah Sebelum Merdeka
Pada tahun 1819 kota Padang diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda (Ramlan Cs: 1995). Sekitar setahun setelah itu, beberapa orang penghulu minta bantuan kepada Belanda untuk mematahkan kekuatan kaum Paderi. Maka pada tanggal 10 Februari 1820 diadakan perjanjian sepihak antara Belanda dengan Sultan Alam Bagagarsyah, Tuanku Saruaso serta beberapa orang penghulu lainnya. Nagari Pagaruyung, Sungai Tarab, Saruaso dan beberapa nagari lainnya kepunyaan Minangkabau diserahkan tanpa syarat. Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa mereka berjanji pada Belanda atas nama sendiri, rakyat maupun keturunannya untuk taat menjalankan segala perintah Belanda tanpa kecuali dan tidak akan menentang satupun, sebaliknya Belanda berjanji membantu memerangi Paderi. Dengan demikian secara de jure kekuasaan Belanda di Minangkabau telah diakui, namun secara de facto baru dua dasa warsa kemudian secara keseluruhan pedalaman Minangkabau dikuasai seluruhnya.
Struktur pemerintahan di Tanah Datar pada awal kekuasaan Belanda yakni: Rakyat-Nagari-Kelarasan-Regenschapen-Hoofd Afdeling. Pada tahun 1837 berubah menjadi: Rakyat-Nagari-Distrik-Controleur-Afdeling. Tahun 1908 struktur pemerintahan berubah lagi, dengan demikian nagari Saruaso menjadi Laras Saruaso, Kecamatan Batusangkar, Afdeling Tanah Datar dengan Kepala Larasnya bernama Saleh Dt. Rajo Malano. Tahun 1914 kembali struktur pemerintahan berubah sehingga menjadi Onderdistrik Saruaso (dengan Padang Ganting) dengan Asisten Demang Said Dt. Rangkayo Basa yang berkedudukan di Tanjung Barulak. Dengan demikian struktur pemerintahan di Tanah Datar adalah: Rakyat-Penghulu-Kepala Nagari-Demang-Controleur-Asisten Residen. Perubahan struktur pemerintahan terakhir di Tanah Datar tahun 1936 yakni: Rakyat-Penghulu-Kepala Nagari-Asisten Demang-Demang- Controleur-Asisten Residen. Susunan pemerintahan seperti ini bertahan sampai masuknya tentara Jepang.
Pada tanggal 15 Maret 1942 Jepang menduduki kota Padang. Dua hari kemudian yakni tanggal 17 Maret 1942 Jepang memasuki kota Batusangkar dan sekitarnya termasuk Saruaso. Kedatangan Jepang disambut gembira rakyat Tanah Datar karena semboyan Jepang yang menarik simpati yakni “Jepang saudara tua, Indonesia saudara muda”, “Jepang datang untuk kesejahteraan Asia”. Saking gembiranya masyarakat meneriakkan kata “Bonzai Nippon” jika bertemu orang-orang Jepang. Propaganda Jepang untuk membenci Belanda dan orang barat lainnya yang ditanamkan dalam masyarakat terkenal dengan slogan “Orang Inggris harus kita linggis, Orang Amerika harus kita seterika, dan orang Belanda harus kita perkuda”.
Untuk memudahkan pengendalian dalam pemerintahan, sementara Jepang melanjutkan model struktur pemerintahan Belanda dengan istilah yang berbeda namun hakikatnya sama. Tanah Datar ketika diperintah Belanda merupakan sebuah Afdeling tetap dipertahankan akan tetapi namanya diganti menjadi Bun atau Luhak yang dipimpin oleh seorang Bun Shucho. Struktur ke bawahnya setelah Bun adalah Fuku Bun (Belanda adalah Kedemangan) yang dikepalai oleh Fuku Buncho. Di bawah Fuku Bun terdapat pula Gun (Belanda adalah Distrik) yang dikepalai oleh Gun cho. Di bawah Gun barulah terdapat Nagari yang dipimpin langsung oleh Kepala Nagari. Untuk membantu Kepala Nagari dalam menjalankan tugasnya dibentuk pula kesatuan kecil dari nagari yaitu rukun tetangga yang disebut dengan Tonari Gumi yang dipimpin oleh Tonari Gumicho. Tonari Gumi inilah yang merupakan kesatuan kecil dari struktur pemerintahan Jepang di Tanah Datar.
Jepang segera melakukan mobilisasi penduduk dengan mengadkan latihan-latihan militer dan membentuk barisan-barisan rakyat seperti Bogodan, Seinendan, Gyugun, dan Heiho. Jepang juga mamajukan pendidikan masyarakat dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti Kokumin Gakko (sekolah rendah), Tyu Gakko (sekolah lanjutan), Sihan Gakko (sekolah normal), Sihan Gakko, Nippon Ge Gakko (sekolah bahasa jepang), Jekyu Shikan Gakko (sekolah latihan guru-guru). Di sekolah tersebut umumnya diberikan pelajaran pemupukan kesetiaan pada Kaisar, semangat berjuang, disiplin, sejarah, ekonomi, ilmu bumi, dan bahasa Jepang. Pelaksanaan pembelajaran diberikan pelajaran semi militer yang mengutamakan disiplin serta pelajaran bahasa Jepang.
Kebijakan di bidang ekonomi diarahkan kepada ekonomi perang melalui pengaturan, pembatasan serta penguasaan semua faktor produksi. Kebijakan itu sangat menyiksa rakyat. Rakyat dikenakan peraturan wajib setor dan wajib tanam. Sebagian besar hasil sawah dan lading dikumpulkan digudang-gudang makanan. Beberapa daerah yang dijadikan gudang tempat penyimpanan makanan adalah Simabur, los di pasar Batusangkar, Lintau, Pitalah, Salimpaung, Saruaso dan pasar Rambatan. Kondisi ini diperparah lagi dengan kerja paksa (romusha) di Logas.
Di bidang pertahanan Jepang banyak membuat benteng-benteng pertahanan berupa pos pengamanan yang sangat tinggi dan lobang-lobang terbuat dari beton, seperti di Simawang, Ombilin, Batusangkar, Saruaso, dan Kumango. Di Saruaso benteng pertahan berupa lobang (masyarakat Saruaso menyebutnya “Lubang jopang”) terletak di kiri kanan jalan Saruaso-Batusangkar, tepatnya di persimpangan jalan ke lapangan Dang Tuanku.
G. Periode Sejarah Sesudah Merdeka
Cerita sejarah sesudah merdeka di Tanah Datar termasuk di Saruaso digambarkan dari beberapa suasana atau keadaan.
Pertama, suasana seputar proklamasi. Setelah kemerdekaan diproklamirkan di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, maka tanggal 29 Agustus 1945 diikuti dengan pernyataan dukungan secara resmi oleh rakyat Sumatera Barat yang ditanda tangani oleh Moehammad Syafei (Kementerian Penerangan Sumatera Tengah). Ramlan Cs. (1995) menulisnya sebagai berikut:
| PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan KEMERDEKAAN INDONESIA Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Maka kami bangsa Indonesia di Sumatera dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjunjung keagungan kedua pemimpin Indonesia. Bukittinggi, 29 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia di Sumatera Moehammad Sjafei |
Berita kemerdekaan disambut rakyat dengan sukacita dengan mengibarkan bendera Merah Putih atau membuat bendera kecil-kecil dari kertas. Di kota Batusangkar, untuk pertama kalinya tanggal 26 Agustus 1945 pukul 17.30 dikibarkan Bendera Merah Putih di “rumah batu” Malana milik ibu Syawaluddin.
Setelah merdeka, pemerintah baru Republik Indonesia berbenah diri dengan mengambil langkah-langkah:
- Membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI)
Panitia Kemerdekaan Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia dari tingkat pusat (KNI) sampai ke tingkat kewedanaan (KNID). KNID merupakan badan perwakilan rakyat yang membantu pekerjaan pemerintah. KNID mengangkat Residen Sumatera Barat sebagai pucuk pemerintahan di Sumatera Barat. Setelah ditetapkan, segera Residen Sumatera Barat membentuk badan-badan pemerintahan, jawatan-jawatan, kepala-kepala luhak, wali kota dan demang. Untuk Batusangkar ditunjuk Saudara Sinyar sebagai Demang. Dalam menjalankan tugasnya, Saudara Sinyar dibantu oleh Asisten Demang yang merupakan kepala Onder Distrik. Ketika itu Saruaso termasuk dalam Onder Distrik Pagaruyung.
Pada tanggal 21 Mei 1946 Residen Sumatera Barat mengeluarkan suatu maklumat tentang susunan pemerintahan nagari, rumah tangga nagari dan cara memilih anggota Dewan Perwakilan dan badan Pemerintahannya. Dengan maklumat tersebut terjadi perubahan sistem pemerintahan nagari dari sistem pemerintahan demokrasi Minangkabau ke sistem demokrasi yang baru.
H. Menyusun kekuatan militer
Langkah yang ditempuh yakni membentuk badan-badan keamanan seperti Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Tentara Pelajar (TP), Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Masyarakat Saruaso tidak luput berjuang dengan menjadi anggota dari badan-badan keamanan yang telah dibentuk.
I. Membentuk Barisan Rakyat
Melalui Barisan Rakyat inilah tumbuh partai-partai seperti Hisbullah, Sabilillah, Lasykar Pesindo, Lasymi, Temi, Barisan Hulu Balang, dan Sabil Muslimat. Masyarakat Saruaso pun tidak luput berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menjadi anggota dari partai-partai yang telah dibentuk.
Kedua, suasana menghadapi agresi Belanda. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata tidak diakui oleh Belanda. Tentara sekutu yang datang ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang diikuti oleh tentara Belanda. Akhirnya Belanda melancarkan agresi tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 19 Desember 1948.
Setelah selesai melaksanakan tugas tentara sekutu ditarik kembali dari Indonesia dan mengumumkan bahwa kedudukan mereka digantikan oleh Belanda.
Sekutu ditarik dari Sumatera Barat tanggal 24 Oktober 1946, namun sebelum itu tanggal 17 Oktober 1946 tentara Belanda telah mendarat di Padang. Kondisi demikian mendapat reksi keras dari Residen Sumatera Barat namun hal tersebut tidak digubris sama sekali. Pertikaian demi pertikaian terjadi yang pada akhirnya Belanda melancarkan serangan militer.
Mula-mula dikuasai kota Padang, kemudian berangsur-angsur Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan akhirnya memasuki kota Batusangkat tanggal 26 Desember 1948.
Pada hari Minggu akhir bulan Desember 1948 terjadi kepanikan di tengah keramaian pasar Saruaso mendengar berita bahwa Belanda akan masuk ke Saruaso. Untuk menyelamatkan diri, masyarakat segera mengungsi ke Sungai Ameh, Talago Gunuang dan Kubang Landai. Orang-orang Batusangkar juga mengungsi ke Kubang Landai. Mereka pada umumnya orang-orang keturunan Keling India. Tanggal 27 Desember 1948 pasukan Belanda memasuki Saruaso. Namun gerakan manjunya dihadang di Batu Bapahek oleh tentara Republik dibawah pimpinan Sersan Edison dan komandan pasukan Belanda ditembak kepalanya. Ketika itu Wali Nagari Perang Saruaso yakni M. Dini Rajo Batuah. Dalam rangka menghambat lajunya pasukan Belanda masuk Saruaso dilakukan beberapa upaya antara lain merusak jembatan Batu Bapahek, membongkar jalan di kelok Malapari dan merobohkan jembatan Lubuak Batapuak.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti minyak tanah, garam, sabun dan lain-lain dibentuk pasar pelarian yang terkenal dengan sebutan Balai Ijok di Talago Gunuang. Balai Ijok Talago Gunuang termasuk balai terbesar ketika itu. Balai Ijok Talago Gunuang ramai didatangi masyarakat Tanah Datar, Solok, Sicincin dan Lubuk Alung.
Penderitaan-penderitaan akibat agresi Belanda sangat dirasakan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Saruaso. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Belanda pun mengakui kemerdekaan Indonesia dan angkat kaki dari negeri tercinta ini.
J. Periode Modern/Terkini
Sebagaimana diungkap di bagian muka, kurang lebih satu tahun setelah merdeka yakni tanggal 21 Mei 1946, Dr. Djamil Dt. Rangkayo Tuo selaku Residen Sumatera Barat mengeluarkan maklumat No. 20-21-46 tentang susunan pemerintahan negeri, rumah tangga negeri dan cara memilih anggota Dewan Perwakilan dan badan Pemerintahannya. Dengan maklumat tersebut terjadi perubahan sistem pemerintahan nagari dari sistem pemerintahan demokrasi Minangkabau ke sistem demokrasi yang baru.
Melalui maklumat tersebut, pimpinan pemerintahan negeri terdiri dari Dewan Perwakilan Negeri, Dewan Harian Negeri dan Wali Negeri. Wali Negeri menjadi ketua Dewan Perwakilan Negeri dan Dewan Harian Negeri.
Berdasarkan prosesi pemilihan Wali Negeri secara langsung oleh seluruh Dewan Perwakilan Negeri, maka tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan M. Dini Rajo Batuah sebagai Wali Negeri Saruaso. Mulai saat itu Dewan Perwakilan Negeri bersama-sama dan dengan dipimpin oleh Wali Negeri menjalankan pekerjaan rumah tangga negeri yang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kurang lebih dua tahun kemudian yakni tanggal 22 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) karena Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda. Tanggal 2 Januari 1949 keluar ketetapan PTTS No. WKS/SJ/LST 038 tentang Pemerintahan Militer untuk daerah Sumatera Barat dan ditunjuk Mr. St. Moh Rasyid sebagai Gubernur Militer. Mr. St. Moh Rasyid segera mengeluarkan Instruksi No. 10/G.54/Instr/1949 tentang pembagian tugas Bupati-Bupati, Wedana-Wedana, Camat dan Wali-Wali Negeri Perang serta menetapkan pejabat Bupati-Bupati di Sumatera Barat. Selanjutnya Bupati Militer segera menetapkan pejabat Wedana, Camat Militer dan Wali-Wali Negeri Perang. Untuk Saruaso ditunjuk Wali Negeri yang ditetapkan Dewan Perwakilan Negeri Saruaso tanggal 1 Juli 1946 yakni M. Dini Rajo Batuah sebagai Wali Negeri Perang.
Pasca ditariknya pasukan Belanda dari Tanah Datar tanggal 17 Desember 1946, dengan penuh rasa syukur, lega dan gembira masyarakat Tanah Datar bersama pemerintah segera berbenah diri. Berangsur-angsur kegiatan pembangunan mengisi kemerdekaan kembali mulai menggeliat. Peristiwa-peristiwa mulai dari penyerahan kekuasaan oleh Belanda, Dekrit Presiden, periode Orde Lama, periode Orde Baru dan periode Reformasi dijalani dengan sabar dan penuh perhitungan.
Semenjak penyerahan kekuasaan oleh Belanda sampai dikeluarkan UU No. 5 Thn. 1979 tentang Pemerintah Desa, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari Saruaso dikoordinasikan oleh beberapa orang wali nagari. M. Dini Rajo Batuah memimpin pemerintah Nagari hingga tahun 1950. Periode 1950-1960 dipimpin oleh A. M. Mathoes. Periode 1960-1963 dipimpin oleh Tamin Dt. Jindo Palowan (Dt.Gapuak). Periode 1963-1965 dipimpin oleh Sahad Dt. Majo Tianso. Periode 1965-1968 dipimpin oleh Juin Dt. Paduko Sarindo. Dilanjutkan oleh Mansur sebagai karateker kurang lebih 3 bulan. Setelah itu Periode 1968-1970 dipimpin oleh Luki Gunuang Ameh. Periode 1970-1975 dipimpin oleh M. Ongku Apan. Periode 1975-1980 kembali dipimpin oleh Luki Gunuang Ameh. Periode 1980-1983 dipimpin oleh Panius Dt. Penghulu Rajo.
Dengan diberlakukan UU No. 5 Thn. 1979 tentang Pemerintah Desa, maka status nagari sebagai unit pemerintahan terendah dalam daerah provinsi Sumatera Barat menjadi sirna dan terhapus. Nagari Saruaso terbagi atas beberapa desa dan masing-masingnya dipimpin oleh Kepala Desa. Periode awal (1980-1991) Saruaso terbagi dalam 9 Desa. Adapun Desa dan Kepala Desa periode awal yakni:
- Desa Kubang Landai dipimpin Afin Bandaro Panjang dan Khairul Asdar
- Desa Talaga Gunung dipimpin Zainuddin Dt. Malano
- Desa Sumpu dipimpin Jamaris Mln. Sulaiman
- Desa Malayu dipimpin Biran Bdr. Kuniang
- Desa Koto Tuo dipimpin Jamari Majo Indo
- Desa Bendang dipimpin Piun
- Desa Mandahiliang dipimpin K. Dt. Cumano
- Desa Kutianyia dipimpin Suman Pono Kayo, dan
- Desa Sungai Ameh dipimpin Rabiin
Selanjutnya periode kedua (1990-1999) Saruaso terbagi dalam 6 desa. Adapun Desa dan Kepala Desa periode kedua yakni:
- Desa Saruaso Barat dipimpin Umbik Sutan Mudo, Sanun St. Pamuncak, dan Enny Marlinda
- Desa Saruaso Utara dipimpin Nazaruddin Khatib
- Desa SaruasoTimur dipimpin Rusli Jamil dan Sy. Dt.Maruhun, SE
- Desa Sungai Ameh dipimpin Rabiin dan Efendi
- Desa Kubang Landai dipimpin Afrizal Khatib Kayo, dan
- Desa Talago Gunuang dipimpin Zulfikar
Perkembangan selanjutnya, diatur melalui Perda Nomor 17 Thn 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan Perda Nomor 17 Thn 2001 maka enam desa di Saruaso digabung dalam satu nagari dan penyelenggaraan pemerintahan dipimpin Wali Nagari serta wilayah administrasi desa berubah menjadi jorong. Semenjak diberlakukan Perda Nomor 17 Thn 2001 Saruaso dipimpin oleh beberapa orang Wali Nagari. Periode 2001-2007 dipimpin Syafril Dt. Maruhun, SE. Periode 2007-2009 dipimpin Faisal Bagindo Khatib sekalu Pj. Periode 2009 dipimpin Enny Marlinda selaku Pj. Periode 2009-2015 dipimpin Suardi Malin Mangkuto, dan Periode 2015 dipimpin Herman Yahya selaku Pj. Sedangkan jorong dipimpin Kepala Jorong dengan personil sebagai berikut:
- Jorong Talago Gunuang dipimpin A. Dt. Lelo dan Ratnawilis, SEi
- Jorong Sungai Ameh dipimpin Awaluddin Malin Sinaro
- Jorong Saruaso Timur dipimpin Syafriandi
- Jorong Saruaso Utara dipimpin Budrianto Khatik Kayo dan Djoni Iskandar
- Jorong Kubang Landai dipimpin Afrizal Khatik Kayo dan Khairul Asdar, dan
- Jorong Saruaso Barat dipimpin J. Malin Sulaiman dan Imrizal Dt. Mangku
Adapun penyelenggaraan adat tetap dibawah koordinasi Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin oleh seorang ketua. Periode 1967-1984 dipimpin Sumin. Dt. Mantiko Sati. Periode 1984-1988 dipimpin Panius Dt. Penghulu Rajo, dan Periode 1988-sekarang dipimpin Bachtiar Burhan Dt. Mantiko Sati.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Bab I pasal 1 ayat (13) disebutkan Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari. KAN mempunyai tugas: a) memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah di Nagari; b) memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari; c) membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda; d) mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan soko, pusoko dan syara’; e) mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji; f) mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap soko dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji; g) membentuk majelis penyelesaian sengketa soko, pusoko dan syara’ yang bersifat ad hock; h) membuat kode etik, yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagari; i) mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional; j) membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah; k) melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari; dan l) bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.